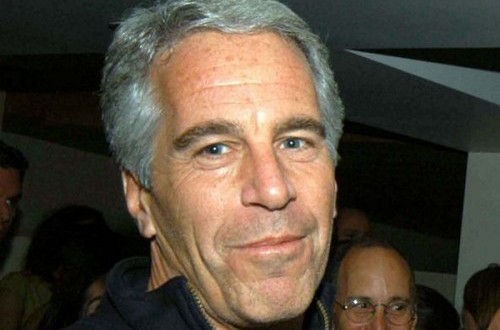REPUBLIKA.CO.ID, Nada bicara Arief terdengar lirih di ujung sambungan telepon. Iramanya lamban. Ia merasakan tubuhnya digelayuti rasa lelah yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Arief tak bisa menjelaskannya. Tapi ia tahu persis apa yang sedang tubuhnya minta. Dia menerjemahkan kelelahan itu sebagai alarm, bahwa waktu cuci darah telah tiba.
Tapi lelah yang dirasa Arief kali ini tak seperti sebelumnya. Seperti terakumulasi. Sudah dua kali jadwal hemodialisis lelaki 34 itu terpaksa tertunda. Sabtu (31/1/2026) atau akhir pekan lalu, sesuai jadwal Arief harusnya menjalani cuci darah. "Pas sampai di rumah sakit katanya BPJS saya sudah nggak aktif," kata dia kepada Republika, Kamis (5/2/2026).
Cuci darah pun tak bisa dilakukan. Perjalanan dari rumah di Desa Purwojati, Kecamatan Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah, menuju Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo hari itu tak ada hasil, meski tak pernah sia-sia. Ia terpaksa kembali ke rumah dengan darah yang belum 'bersih'. Ragam kekhawatiran pun membekap pikiran Arief sepanjang perjalanan pulang.
Ayah satu anak itu divonis dokter mengalami gagal ginjal pada 2021. Sejak saat itu atau selama lima tahun terakhir, cuci darah tak pernah putus ia jalani. Jadwalnya rutin dua kali sepekan, Rabu dan Sabtu. Tetapi pada Sabtu dan Rabu terakhir, aktivitas itu terhenti. "Mungkin racun di tubuh saya menumpuk. Karena kan darah saya baru bisa bersih kalau HD (hemodialisis)," ujar Arief mencoba menjelaskan lelah yang dialaminya.
Terdaftar PBI
Awal ketika divonis gagal ginjal, ia membayar biaya cuci darah secara mandiri. Sekali cuci darah, ia harus merogoh Rp 1,5 juta. Jumlah yang sangat besar untuk seorang pedagang sayur keliling di kampung kecil. Satu kali cuci darah adalah rata-rata penghasilan Arief satu bulan. 'Bagaimana bayarnya jika sebulan harus delapan kali cuci darah.' Pertanyaan itu yang pertama terlintas ketika Arief tahu biaya hemodialisis.
Biaya mandiri hanya mampu dilakukan Arief tidak lebih dari lima kali. Ia lantas mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Arief pun terdaftar di Kelas III dengan membayar premi tiap bulan secara rutin dan tertib. Sejak saat itu, tak lagi pernah ia membayar biaya cuci darah. Semua di-cover penuh BPJS Kesehatan.
Lambat laun, biaya premi BPJS Kesehatan itu mulai menjadi beban baginya. Nominalnya memang tak lebih dari Rp 50 ribu per bulan. Bagi sebagian orang jumlah itu terdengar relatif tidak besar. Tapi bagi Arief, situasinya lain.
Sejak divonis gagal ginjal, kondisi badannya tidak lagi memungkinkan untuk bekerja sebagai tukang sayur keliling. Sempat ia mencoba menjadi tukang pijat dari pintu ke pintu di kampungnya demi pemasukan keluarga. Sekecil mungkin hasilnya, menjadi sangat besar artinya untuk sebuah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Itu pun kini tak lagi mampu ia jalani. Tangan dan jemarinya terus melemah dan tak lagi punya daya.
Sampai pada akhirnya, Arief didaftarkan kepala dusun setempat untuk dimasukkan dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Itu artinya, biaya iuran ditanggung pemerintah. Cuci darah gratis, premi BPJS pun tak lagi menjadi beban Arief.
Tapi Sabtu (31/1/2026) siang pekan lalu bak godam sedang menghantamnya. Mendengar BPJS-nya tak lagi aktif, Arief merasa dipukul dua kali. Pertama oleh tuntutan keharusan cuci darah, yang ini tentang kelanjutan hidupnya. Kedua oleh keadaan yang membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Karena kini tak lagi ada kemungkinan baginya membayar biaya cuci darah secara mandiri di tengah segala keterbatasan yang ada. "Kami (anak dan istri) makan saja sekarang ikut orang tua," ujar dia.
Arief tak pernah tahu alasan ia tiba-tiba dikeluarkan dari PBI BJPS Kesehatan. Tak pernah juga ada informasi sebelumnya sampai pihak RS PKU Muhammadiyah Wonosobo memberi tahu bahwa BPJS-nya tidak lagi aktif. Semua datang tiba-tiba. Ia hanya disarankan oleh pihak rumah sakit untuk mengaktifkan kembali BPJS-nya.
Senin (2/2/2026), ia datang ke mal pelayanan publik di Wonosobo. Segala syarat administratif yang diminta sudah ia penuhi. "Saya hanya berharap cepat aktif dan bisa cuci darah lagi, badan saya sudah sakit semua," kata Arief. Ia kini menggantungkan harapan itu bisa terwujud selekasnya dengan kepasrahan sepenuhnya.
Hal yang sama dirasakan oleh Ajat (37 tahun), seorang pedagang es keliling asal Lebak, Banten, yang menjalani perawatan di RSUD Dr Adjidarmo Rangkasbitung. Ajat terpaksa harus berurusan dengan birokrasi yang berbelit saat dirinya sedang dalam kondisi lemas pasca-tindakan medis.
"Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS tidak aktif. Istri saya harus menempuh perjalanan satu jam ke kelurahan, kecamatan, hingga dinsos, tapi ditolak dan disuruh pindah ke jalur mandiri," ujar Ajat.
Bagi Ajat dan banyak pasien kurang mampu lainnya, berpindah ke BPJS mandiri adalah kemustahilan. "Untuk ongkos ke rumah sakit saja sudah susah, apalagi harus bayar iuran setiap bulan. Saya jualan es, sekarang malah sedang tidak dagang karena musim hujan. Kami hanya ingin sehat, jangan disusahkan seperti ini," kata dia.
Puluhan pasien

 2 hours ago
2
2 hours ago
2