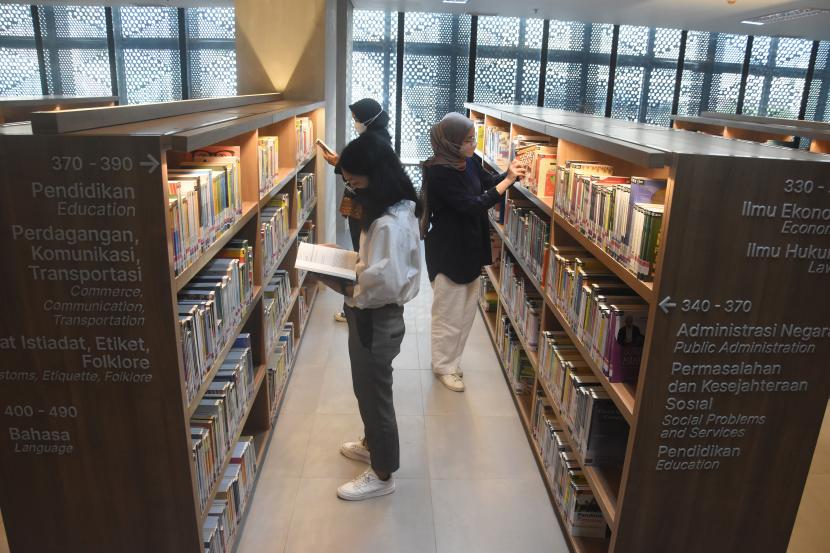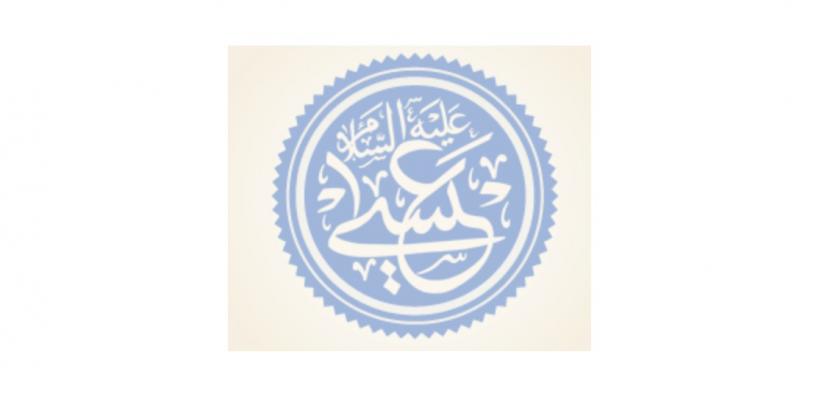Sejarah bukan sekadar masa lalu. Ilustrasi. Foto : republika
Sejarah bukan sekadar masa lalu. Ilustrasi. Foto : republika
Oleh : Yenny Narny, (FIB Unand)
Di tengah geliat zaman yang terus berubah, sejarah seharusnya menjadi ruang refleksi yang jujur—bukan sekadar etalase narasi yang dibentuk dari sudut pandang penguasa. Namun, langkah pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk merevisi sejarah Republik Indonesia justru menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan sejarawan. Bukan karena sejarah tak boleh ditinjau ulang, melainkan karena revisi yang dilakukan ini dikhawatirkan akan mengarah pada pembentukan narasi tunggal yang menyederhanakan kenyataan, menyingkirkan kompleksitas, dan menutupi luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh.
Salah satu bab tergelap dalam sejarah bangsa ini adalah tragedi 1965—peristiwa berdarah yang menelan ratusan ribu korban, menghancurkan kehidupan banyak keluarga, dan menyisakan trauma antargenerasi. Meski lebih dari lima dekade telah berlalu, bayang-bayang tragedi itu masih pekat membekas, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi episentrum kekerasan, seperti Sumatera Barat. Di sana, sejarah tidak sekadar menjadi catatan di buku, tetapi hadir sebagai luka yang diwariskan secara diam-diam dari orang tua kepada anak-anak mereka, bahkan untuk menyebutkan nama secara terangpun mereka engan.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Ambil contoh Roza, seorang ibu rumah tangga yang lahir pada tahun 1979 di Padang. Ia bukan bagian dari peristiwa 1965 secara langsung, tapi kehidupannya ditentukan oleh tragedi itu. Ayahnya adalah salah satu pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatera Barat yang ditangkap dan disiksa secara brutal—hingga jempolnya copot. Selama lebih dari 13 tahun, ia dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, sementara seluruh harta bendanya dirampas. Ibunya pun tak luput dari derita: tidur di lantai berkerikil beralas tikar pandan, ditemani anak balitanya di balik jeruji besi.
Yang membuat luka itu semakin dalam bukan hanya penderitaan fisik atau kehilangan harta benda, tetapi juga stigma yang terus memburu anak-anak mereka. Di sekolah, Roza mendapat label yang tak pernah ia pilih: anak pemberontak. Ia menjadi sasaran cemoohan, bahkan dari para guru. Namun, Roza memilih untuk tidak bungkam. Ia tumbuh dengan keberanian untuk mempertanyakan kembali versi sejarah yang selama ini diajarkan—bukan untuk membela, melainkan untuk mencari kebenaran yang tertimbun. Baginya, PKI adalah partai politik sipil yang dibungkam secara sistematis, sementara pengambilalihan kekuasaan justru dilakukan oleh mereka yang kini menulis ulang sejarah.
Kisah serupa juga dialami Dahliar. Bahkan ketika ia lahir, ayahnya sudah ditahan. Hidup dalam kemiskinan, ia terpaksa berhenti sekolah di kelas empat SD. Bukan karena malas, tapi karena harus membantu keluarga bertahan hidup. Label “anak PKI” melekat kuat pada dirinya, cukup hanya karena sang ayah pernah menerima sekotak beras. Namun Dahliar tidak tumbang. Ia menjadikan kepahitan hidup sebagai pelajaran tentang daya tahan dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Dan kemudian ada Dwi. K, yang lahir tepat di tahun kelam itu—1965. Ia menyaksikan langsung bagaimana ibunya harus bekerja demi sebutir beras, dan dirinya yang masih kecil harus belajar bertahan dengan makan bubur tiris. Ketika dewasa dan seorang tentara hendak melamarnya, semua rencana pupus hanya karena label keluarga eks-PKI. Meski dunia menolaknya karena masa lalu yang bukan pilihannya, Dwi tidak pernah menyesali asal-usulnya. Ia memilih hidup dengan kepala tegak.
Dari kisah mereka, satu hal menjadi terang: sejarah bukan sekadar masa lalu. Ia hidup dalam tubuh dan jiwa mereka yang menanggung warisan luka. Maka ketika negara ingin menyusun ulang catatan sejarahnya, pertanyaan terbesarnya adalah: untuk siapa narasi itu dibuat? Jika revisi hanya untuk memperkuat satu versi kebenaran, lalu siapa yang akan mendengar suara mereka yang selama ini dibungkam?
Narasi tunggal bukan hanya problem akademik, tapi ancaman nyata bagi upaya bangsa ini untuk berdamai dengan masa lalunya. Ia bisa menyapu bersih jejak-jejak luka, lalu menggantikannya dengan ilusi ketertiban yang dibangun di atas penderitaan yang disangkal. Padahal, rekonsiliasi sejati tidak mungkin lahir dari pengingkaran.
Sejarah bukan sekadar mengingat, ia menuntut keberanian untuk mengakui, mendengarkan, dan membuka ruang bagi mereka yang dulu dilabeli, ditindas, dan disisihkan. Kalau bangsa ini benar-benar ingin berdamai dengan sejarahnya, maka langkah pertama yang paling manusiawi adalah memberi ruang bagi narasi yang selama ini terpinggirkan. Bukan untuk membenarkan masa lalu, tapi untuk memberi keadilan pada mereka yang selama ini hanya diminta diam. (*)
Penulis adalah Profesor di bidang Sejarah Sosial dan mengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

 4 hours ago
3
4 hours ago
3